Oleh:
Husin Ali
Ketika ribuan anak muda dari seluruh penjuru negeri menjejakkan kaki di tanah lapang Bumi Perkemahan Bongohulawa, mereka sebenarnya sedang melangkah ke dalam ruang sosial yang unik.Tanah berbukit di jantung Limboto itu tidak hanya menjadi tempat tenda-tenda berdiri, melainkan juga ruang simbolik tempat nilai-nilai kebangsaan dihidupkan kembali — tanpa slogan, tanpa seremoni, tanpa instruksi.
Dari tepuk riuk tepuk Pramuka dan derap langkah para penegak, kita bisa mendengar denyut sosial yang sesungguhnya: Indonesia yang belajar untuk saling memahami.
Bongohulawa, Tanah yang Setia kepada Pramuka
Bongohulawa bukanlah lokasi yang asing bagi Gerakan Pramuka.Sejak tahun 2006, tanah ini telah tiga kali dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan nasional :Perkemahan Wirakarya Nasional 2006, Pertisaka Bakti Husada Nasional 2011, dan kini Peran Saka Nasional 2025. Dalam rentang hampir dua dekade itu, satu hal tetap sama — kerendahan hati Gorontalo dalam menyambut Indonesia.
Di banyak tempat, kegiatan nasional sering diidentikkan dengan kemegahan: tenda besar, panggung tinggi, dan teknologi. Namun Bongohulawa selalu mengajarkan hal lain: bahwa keindahan tak selalu berdiri di balik dekorasi, melainkan di dalam interaksi manusia yang tulus.
Bongohulawa bukan hanya lokasi, melainkan memori kolektif kepanduan Indonesia — tempat di mana generasi muda datang bukan untuk ditonton, tapi untuk membangun kebersamaan.
Di lereng yang menantang dan tanah yang hijau, Pramuka Indonesia berlatih arti kemandirian dan tanggung jawab.Setiap tenda yang tegak di atas bukit menjadi simbol kemampuan manusia berdamai dengan alam. Dan di setiap tawa anak muda di bawah langit Gorontalo, kita melihat kembali cita-cita pendiri bangsa — membentuk manusia merdeka yang kuat secara moral dan sosial, bukan sekadar pintar secara formal.
Antropologi Bongohulawa: Ruang Simbolik dan Ritual Kebangsaan
Dalam kajian saya sebagai seorang antropolog, kegiatan seperti Perkemahan Pramuka adalah bentuk ritual kebangsaan — sebuah ruang di mana individu-individu dari latar belakang berbeda menjalani proses liminal, atau peralihan identitas.
Mereka datang sebagai peserta dari daerah yang beragam, lalu keluar dengan identitas baru sebagai bagian dari bangsa. Ritual ini penting karena di situlah makna kebangsaan yang hidup terus diperbarui dari generasi ke generasi.
Bongohulawa menjadi wadah ideal bagi proses itu. Bentang alamnya yang menantang mengajarkan kesabaran; kearifan lokal masyarakat Gorontalo yang ramah memperlihatkan cara paling sederhana untuk menghormati perbedaan.Di tanah inilah, teori antropologi sosial menemukan buktinya: bahwa identitas nasional tidak dibangun dari keseragaman, melainkan dari interaksi lintas perbedaan yang tulus.
Nilai “huyula”, kerja bersama tanpa pamrih, menjadi roh dari pengalaman ini. Ia tidak diajarkan dalam forum resmi, tetapi dijalani di dapur umum, di regu yang saling menolong, di panitia lokal yang tersenyum ketika membantu peserta dari luar daerah. Nilai itu adalah manifestasi paling konkret dari Pancasila yang hidup, bukan sekadar dihafalkan.
Saka dan Krida: Wajah Praktis Pendidikan Karakter
Gerakan Pramuka lewat Satuan Karya (Saka) dan kridanya sesungguhnya adalah model pendidikan karakter paling antropologis yang dimiliki Indonesia.Ia tidak mengandalkan teori, tetapi pembiasaan budaya — cara belajar dengan bekerja, cara berpikir dengan berbuat.
Di Bongohulawa, anak muda belajar kedisiplinan di Saka Bhayangkara, empati kemanusiaan di Saka Bakti Husada, keseimbangan ekologis di Saka Kalpataru, keberanian di Saka Wira Kartika, hingga nilai keluarga di Saka Kencana.Semua itu menjadi ruang praksis bagi nilai-nilai sosial bangsa yang kerap hilang di ruang formal pendidikan.
Pramuka, dalam kacamata antropologi pendidikan, adalah reproduksi sosial nilai-nilai bangsa: kejujuran, kesetiaan, gotong royong, dan tanggung jawab.Dan Bongohulawa menjadi panggung tempat nilai-nilai itu tidak hanya diajarkan, tetapi dihidupkan kembali.
Gorontalo: Kota Ramah dan Panggung Kemanusiaan
Bongohulawa tidak dapat dipisahkan dari denyut kehidupan Kota Gorontalo, tempat keramahan dan kesahajaan menjadi fondasi peradaban lokal.Kota ini kini menjelma menjadi magnet sosial baru Indonesia Timur — kota kecil yang tidak berkompetisi untuk menjadi paling modern, tetapi paling manusiawi.
Membaca tulisan di RGOL.id, orang Gorontalo perantauan kini “rindu pulang”.Di mana pun mereka berada, selalu ada cerita tentang trotoar yang ramai dengan anak muda, tentang pasar yang hidup tanpa kebisingan, tentang senyum yang tidak kering oleh waktu.Kerinduan itu adalah indikator sosial yang penting — menandakan bahwa kota ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat kembali.
Kebijakan dan langkah-langkah sosial di kota ini memperlihatkan orientasi baru terhadap manusia.Penataan ruang publik yang membuka peluang ekonomi dan interaksi warga menjadikan Gorontalo sebagai contoh urbanisme yang berjiwa.Ruang publik di sini tidak hanya diisi oleh beton dan kendaraan, tetapi oleh tawa, sapaan, dan percakapan antar manusia. Dalam istilah antropologi perkotaan, inilah bentuk kota yang etis, tempat pembangunan dan kemanusiaan tidak berjalan di jalur yang terpisah.
Bongohulawa sebagai Cermin Indonesia
Kwartir Nasional tampaknya memahami sesuatu yang mendalam ketika kembali memilih Gorontalo sebagai tuan rumah.Pilihan ini bukan semata soal lokasi yang strategis atau fasilitas yang lengkap, tetapi tentang makna sosial yang ingin dihidupkan kembali.
Selama ini, miniatur Indonesia sering dipusatkan di Cibubur, Jakarta.Namun Bongohulawa membuktikan bahwa miniatur Indonesia tidak harus di pusat, ia bisa hidup di daerah yang menjaga nilai gotong royongnya dengan tulus.
Bongohulawa adalah cermin kecil dari Indonesia besar — di mana ribuan anak muda bisa hidup dalam perbedaan tanpa kehilangan rasa hormat.Di sinilah negara hadir tanpa birokrasi, dan nasionalisme hidup tanpa instruksi.
Dari Gorontalo untuk Indonesia
Gorontalo telah menulis bab penting dalam narasi kebangsaan melalui jalan yang lembut: pendidikan moral melalui budaya, pembangunan melalui keramahan, dan kebersamaan melalui tindakan kecil yang berulang. Ia menunjukkan bahwa kota kecil pun bisa berperan besar, asalkan tetap menjaga hati manusianya.
Sebagai antropolog, saya melihat Bongohulawa bukan hanya bumi perkemahan, tetapi laboratorium sosial bangsa ini.Tempat di mana nilai kebangsaan diuji dan diperbarui, bukan dengan upacara, melainkan dengan hidup bersama.
Dan Gorontalo, dengan kehangatan manusianya, menjadi wajah paling jujur dari Indonesia yang kita rindukan — Indonesia yang ramah, seimbang, dan saling percaya. Di tanah lapang Bongohulawa, Indonesia tidak sedang berkemah —ia sedang belajar pulang ke dirinya sendiri. (*)
Penulis adalah adalah antropolog, peneliti budaya lokal, dan
Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Gorontalo.













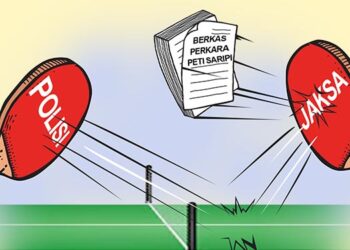

Discussion about this post