Oleh:
Hasim
Pariwisata alam menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan wilayah dengan karakteristik geografis pesisir dan laut yang kuat seperti Gorontalo. Namun, dinamika pemulihan pasca pandemic menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pertumbuhan ekonomi pariwisata dan kapasitas ekologi destinasi. Persoalan umum yang dihadapi Gorontalo adalah kesenjangan antara narasi “destinasi wisata alam unggulan” dan kerangka objektif untuk mengukur dampak sosial–lingkungan dari pertumbuhan sektor tersebut.
Ketika indikator pembangunan hanya menonjolkan angka PDRB, tingkat hunian kamar, dan lama menginap, maka terdapat risiko bahwa keberhasilan yang dicapai bersifat parsial dan tidak mencerminkan keberlanjutan ekosistem maupun kesejahteraan komunitas. Dalam konteks ini, pertanyaan kritisnya bukan sekadar seberapa besar pertumbuhan ekonomi pariwisata, tetapi seberapa jauh pertumbuhan tersebut berlangsung tanpa mengorbankan asset ekologis yang menjadi fondasinya.
Data PDRB Gorontalo menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada kategori Jasa Akomodasi dan Makan Minum, dari sekitar Rp 964 miliar (2020) menjadi Rp 1,25 triliun (2024). Tren ini selaras dengan peningkatan malam kamar terpakai pada hotel berbintang, yang naik dari kisaran 86.000 (2021) menjadi lebih dari 109.000 malam (2024). Peningkatan ini menandakan bahwa kegiatan ekonomi pariwisata, terutama yang berbasis akomodasi formal, berkembang cukup kuat. Aparat daerah dapat menafsirkan hal ini sebagai bukti bahwa Gorontalo memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan baru, bahkan sebagai engine percepatan ekonomi daerah.
Namun, jika ditelusuri lebih dalam, struktur pertumbuhan ini bersifat kota-sentris (urban concentrated): nilai ekonomi pariwisata paling banyak terkonsentrasi di Kota Gorontalo, sementara kabupaten-kabupaten dengan potensi wisata alam tinggi; Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara, masih menunjukkan malam menginap dan hunian kamar yang rendah. Artinya, nilai ekonomi dari sumber daya alam pesisir dan laut justru lebih banyak “terperangkap” di pusat kota, bukan di wilayah sumber daya tersebut berada.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan stratifikatif: apakah pertumbuhan pariwisata Gorontalo benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan komunitas pesisir, ataukah hanya menguatkan struktur ekonomi yang timpang? Studi ekowisata global menunjukkan bahwa pariwisata alam hanya membawa manfaat signifikan apabila tiga kondisi terpenuhi: (1) adanya local ownership dan local control atas usaha wisata; (2) system pembagian manfaat yang adil; dan (3) perlindungan ekosistem yang terukur dan diawasi. Tanpa ketiga elemen tersebut, sektor pariwisata alam mudah berubah menjadi model ekstraksi nilai yang mengandalkan lanskap ekologis, tetapi tidak memberikan imbal balik memadai bagi penjaga lanskap tersebut.
Ancaman terhadap ekowisata Gorontalo dapat ditinjau dari dua dimensi: ekologis dan kelembagaan. Dari sisi ekologis, kawasan penyelaman, terumbu karang Teluk Tomini, dan ekosistem mangrove pesisir rentan terhadap tekanan kunjungan yang tidak terkelola dengan baik. Ketika rata-rata lama menginap tetap rendah (sekitar 1,4 hari) sementara promosi “wisata bahari” meningkat, muncul fenomena high turnover – low appreciation, yaitu wisatawan melakukan aktivitas eksplorasi cepat tanpa proses edukasi, interpretasi, dan konservasi yang memadai. Dalam banyak destinasi, pola kunjungan semacam ini berhubungan dengan meningkatnya volume sampah laut, kerusakan karang akibat aktivitas snorkeling massal, serta tekanan terhadap spesies endemik. Tanpa kebijakan daya dukung lingkungan (carrying capacity) dan zonasi konservasi berbasis bukti, pertumbuhan pariwisata dapat menggerus capital ekologis daerah.
Dari sisi kelembagaan, Gorontalo menghadapi lemahnya integrasi antara sektor pariwisata dan sektor lingkungan. Sistem statistic daerah belum memasukkan indikator ekologis seperti tingkat tutupan karang, kualitas air laut, atau kapasitas dukung lokasi wisata. Ketidakhadiran indikator ini membuka ruang bagi interpretasi keliru: peningkatan PDRB dianggap sebagai bukti keberhasilan ekowisata, padahal secara ekologis mungkin terjadi degradasi yang tak terukur? Ketidak sinkronan antara data ekonomi dan data ekologis ini menjadi pra-kondisi structural bagi munculnya greenwashing tourism.
Risiko greenwashing dalam pariwisata tampak pada meningkatnya penggunaan label “eco”, “green”, “bahari berkelanjutan”, atau “desa wisata ekologis” dalam promosi destinasi, padahal belum ada mekanisme sertifikasi, audit lingkungan, dan system pelaporan dampak yang kredibel. Hotel berbintang dapat mengklaim dirinya “ramah lingkungan” hanya dengan mengurangi penggunaan sedotan plastik, sementara konsumsi energi, manajemen limbah, dan pengadaan pangan tetap mengikuti pola konvensional. Operator tur dapat menjual paket wisata mangrove dengan narasi konservasi, padahal pembangunan fasilitas wisata justru berdampak pada alih fungsi zona riparian. Komunitas lokal dapat diikutsertakan secara simbolik sebagai pemandu, namun tidak diberi porsi pengambilan keputusan strategis. Semua itu adalah pola yang secara teoritis dikenal sebagai symbolic sustainability: keberlanjutan dalam simbol, bukan dalam substansi.
Untuk menghindari jebakan greenwashing, Gorontalo membutuhkan paradigm baru berupa Ecological–Economic Integrated Tourism System (EEITS). Model ini mengharuskan setiap klaim “green” ditopang oleh tiga pilar: (1) indikator ekologis berbasis sains (tutupan karang, polusi mikro plastik, indeks kualitas ekosistem pesisir); (2) indikator sosial berbasis keadilan (local ownership rate, community benefit index); dan (3) indikator ekonomi berbasis nilai tambah lokal (proporsi pendapatan yang kembali ke desa wisata). Dengan model ini, PDRB tidak lagi dibaca sebagai satu-satunya indikator, tetapi dikombinasikan dengan metrik ekologis dan sosial sehingga memberikan gambaran utuh tentang keberlanjutan.
Secara komparatif, daerah seperti Raja Ampat, Wakatobi, dan Lombok Utara telah menerapkan model serupa melalui skema izin kunjungan, kontribusi konservasi, dan audit ekowisata berkala. Gorontalo dapat mengadaptasi pendekatan ini dengan menciptakan Gorontalo Sustainable Tourism Observatory—sebuah pusat pemantauan berbasis data yang mengintegrasikan laporan dari dinas pariwisata, dinas lingkungan, akademisi, dan komunitas lokal.
Dengan demikian, Gorontalo memiliki potensi besar dalam wisata alam, tetapi tanpa desain kelembagaan yang kuat dan indikator ekologis yang terukur, pertumbuhan tersebut berisiko terjebak dalam greenwashing tourism. Langkah strategis kedepan bukan hanya mengembangkan destinasi baru, tetapi membangun system pariwisata yang benar-benar hijau—yang hijau dalam data, hijau dalam praktik, dan hijau dalam manfaat. (*)
Penulis adalah Pengajar Ekologi dan Lingkungan di UNG













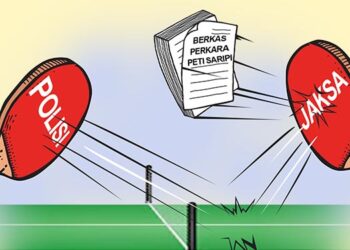

Discussion about this post